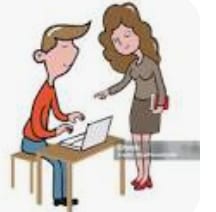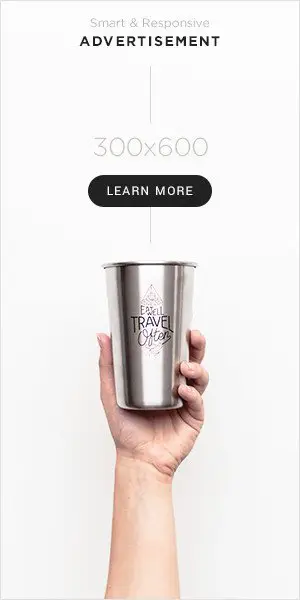Ketika pemerintah mengumumkan program digitalisasi pendidikan lewat pengadaan 1,1 juta unit laptop untuk sekolah, banyak yang menyambut dengan harapan. Ini terdengar seperti lompatan besar: menjembatani ketimpangan digital, mendukung Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), dan memberi alat belajar yang setara ke seluruh Indonesia. Tapi seperti banyak program besar lainnya, kenyataan di ruang kelas tidak semegah konferensi persnya.
Laptop-laptop itu, sebagian besar Chromebook, dikirim ke sekolah-sekolah negeri dengan janji peningkatan mutu. Tapi apa gunanya perangkat canggih tanpa sinyal, tanpa listrik stabil, tanpa pelatihan, dan tanpa pertimbangan kebutuhan sesungguhnya? Di banyak desa, perangkat hanya disimpan di lemari kepala sekolah karena guru tak tahu cara menggunakannya, dan siswa tak bisa akses konten karena tak ada jaringan. Ironis, alat bantu belajar berubah menjadi pajangan mahal.
Program senilai Rp 9,9 triliun itu kini menjadi bahan penyelidikan Kejaksaan Agung dan KPK. Empat pejabat dan konsultan telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk staf khusus menteri. Tuduhan mencakup maladministrasi, mark-up harga, dan pembatasan vendor pada perusahaan tertentu. Dugaan bahwa satu unit laptop dihargai hingga Rp10 juta lebih mahal dari harga pasar memunculkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang belajar dari proyek ini?
Klarifikasi datang: menteri menyatakan harga itu termasuk aksesoris, pelatihan, dan layanan pendukung. Tapi publik berhak bertanya: mengapa spesifikasi tak sesuai realita lapangan? Mengapa vendor tertentu dipilih tanpa transparansi? Dan mengapa peringatan teknis internal sejak 2019 bahwa Chromebook tak cocok untuk daerah 3T diabaikan begitu saja?.
Esensi pendidikan adalah memberi alat agar manusia berkembang. Tapi saat alat itu ditentukan oleh proses yang tak transparan, maka yang berkembang bukan manusia melainkan kesenjangan. Digitalisasi tanpa sensitivitas sosial justru memperdalam jurang: sekolah kota bisa memaksimalkan, sementara sekolah desa hanya bisa menonton dari balik jendela lab komputer yang terkunci.
Di balik pengadaan raksasa ini, ada guru yang tetap mengajar dengan kapur dan papan karena belum dilatih perangkat digital. Ada siswa yang lebih nyaman membaca buku bekas daripada mengutak-atik sistem operasi asing yang tak bisa diakses tanpa internet. Dan ada kepala sekolah yang bingung menjawab saat ditanya, “Untuk apa dikirim laptop, jika bahkan pelajaran daring saja tak pernah kami jalankan?”.
Kisah ini mencerminkan masalah yang lebih dalam: kebijakan pendidikan sering kali tidak dibangun dari ruang kelas, melainkan dari ruang rapat. Ia disusun oleh tangan yang tak pernah mencicipi dinginnya kelas pagi atau melihat murid tertidur karena kelaparan. Akibatnya, solusi yang dibangun tak menjawab kebutuhan, melainkan memoles citra institusi.
Kita hidup di zaman ketika kebijakan harus cepat, anggaran harus besar, dan program harus terlihat “maju.” Tapi kemajuan sejati tidak datang dari teknologi yang ditumpuk, melainkan dari pemahaman atas kenyataan hidup yang dihadapi siswa dan guru. Program pendidikan tidak bisa dijalankan seperti proyek infrastruktur karena manusianya lebih kompleks dari jalan tol.
Kasus laptop ini bukan hanya soal korupsi anggaran, tapi korupsi kepekaan. Ini pengkhianatan terhadap janji bahwa setiap anak punya hak belajar dengan layak. Ini tamparan bagi idealisme digitalisasi yang terlalu percaya pada perangkat dan lupa pada konteks.
Jika laptop-laptop itu kini berdebu di sudut ruang guru, maka yang paling rusak bukan perangkatnya, tapi kepercayaan: bahwa pendidikan bisa jadi tempat kita untuk bertumbuh, bukan ladang orang lain mengeruk untung.
*) Dr. Dra. Daswatia Astuty, M.Pd. Penulis adalah Pegiat literasi, Penasihat RVL, Pemerhati Pendidikan, Pekerja Sosial Kemanusiaan, Pelukis dan penulis dengan 50 judul buku lebih, Karya terakhir “Kartini Masa Kini” 45 Tangan Menahan Cahaya.