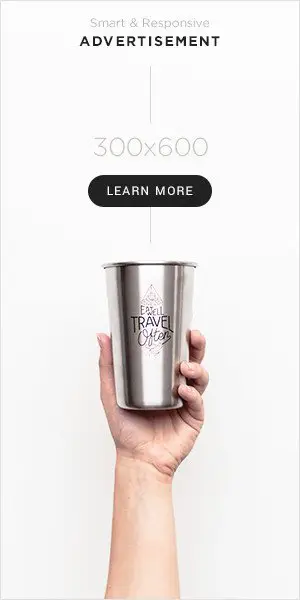Oleh T.H. Hari Sucahyo *)
Ketika Presiden Prabowo Subianto menyatakan ambisinya untuk mencapai swasembada energi dalam lima tahun ke depan dengan mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), publik dihadapkan pada visi besar yang memancarkan optimisme. Strategi utamanya adalah menggenjot produksi biodiesel sebagai pengganti dominan BBM fosil. Dalam narasi politik, gagasan ini terdengar patriotik dan menjanjikan kemandirian.
Dari sudut pandang ekonomi energi dan keberlanjutan, pendekatan ini menyimpan tantangan kompleks yang tak bisa diabaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjalankan program mandatori biodiesel, mulai dari B20 hingga B35, dan pemerintah bahkan merencanakan B40. Program ini memang memberikan kontribusi dalam mengurangi impor solar dan memperbaiki neraca perdagangan.
Capaian tersebut baru menyentuh sebagian kecil dari total konsumsi BBM nasional, yang mayoritasnya masih berasal dari bensin dan avtur, bahan bakar yang belum memiliki substitusi nabati yang seefisien dan sepraktis biodiesel untuk solar. Kita juga tidak boleh lupa bahwa konsumsi BBM di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan industrialisasi.
Tanpa langkah serius dalam efisiensi energi dan diversifikasi teknologi, peningkatan produksi biodiesel bisa dengan cepat tertelan oleh lonjakan permintaan. Artinya, mengejar swasembada energi hanya dengan meningkatkan pasokan tanpa mengendalikan konsumsi adalah pendekatan setengah matang. Dari sisi pasokan, biodiesel bergantung hampir sepenuhnya pada minyak sawit.
Indonesia memang produsen CPO terbesar di dunia, tetapi sebagian besar produksinya juga dialokasikan untuk ekspor dan kebutuhan domestik lain seperti pangan, kosmetik, dan industri oleokimia. Peningkatan permintaan sawit untuk biodiesel berpotensi menimbulkan ketegangan antar-sektor dan memicu lonjakan harga pangan, sebagaimana terjadi saat kelangkaan minyak goreng melanda beberapa waktu lalu. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem logistik dan regulasi kita ketika satu komoditas dijadikan tumpuan terlalu besar dalam berbagai sektor sekaligus.
Selain itu, orientasi yang terlalu berat pada sawit membuka ruang kerentanan ekologis. Alih fungsi hutan demi ekspansi kebun sawit menimbulkan konsekuensi deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi karbon dalam jumlah besar. Sebuah ironi ketika transisi energi justru dilakukan dengan cara yang merusak lingkungan. Indonesia telah dikritik di forum internasional karena lemahnya pengawasan terhadap konversi hutan untuk perkebunan.
Jika swasembada energi ditempuh lewat jalur ini, bukan mustahil kita justru menciptakan krisis iklim yang lebih dalam. Dalam dimensi kebijakan publik, pendekatan tunggal berbasis biodiesel juga belum didukung oleh regulasi komprehensif yang menjamin keberlanjutan. Skema insentif untuk produsen biodiesel sejauh ini lebih menguntungkan korporasi besar, bukan petani kecil.
Di sisi lain, belum ada kerangka kuat yang mengintegrasikan produksi biodiesel dengan strategi perlindungan lahan, hak-hak masyarakat adat, dan konservasi hutan. Alih-alih menciptakan ketahanan energi yang adil, kita bisa berakhir memperbesar ketimpangan struktural yang telah lama mencengkeram sektor agraria dan energi kita. Aspek geopolitik energi juga layak diperhitungkan.
Impor BBM selama ini memang membuat Indonesia bergantung pada pasar minyak global. Namun, ketergantungan pada sawit juga tidak bebas risiko. Jika negara tujuan ekspor utama seperti Uni Eropa memperketat standar lingkungan dan menolak CPO yang dianggap tidak berkelanjutan, maka ekspansi sawit untuk biodiesel bisa menimbulkan konflik diplomatik dan kerugian ekonomi besar. Apalagi, bila pasar ekspor runtuh, pasokan dalam negeri akan dibanjiri oleh CPO yang tak terserap, yang justru akan membebani pemerintah.
Swasembada energi seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan memproduksi sendiri energi secara fisik, melainkan juga sebagai kemampuan mengelola sistem energi secara berdaulat, adil, dan adaptif. Diversifikasi sumber energi menjadi kunci. Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi surya, panas bumi, angin, bahkan gelombang laut. Sayangnya, investasi dan insentif terhadap sektor-sektor ini masih sangat minim dibanding sektor bioenergi.
Kebijakan energi nasional tampaknya belum cukup progresif dalam merangkul spektrum teknologi masa depan. Apabila kita mencermati tren global, masa depan energi tidak terletak pada biofuel, melainkan pada elektrifikasi dan energi bersih tanpa emisi. Negara-negara seperti Jerman, China, bahkan India sedang berlomba-lomba mendorong kendaraan listrik, meningkatkan kapasitas baterai, dan memperkuat jaringan listrik pintar.
Dalam konteks ini, terlalu mengandalkan biodiesel bisa membuat Indonesia tertinggal dalam transformasi teknologi energi global. Lebih jauh, dari sisi ekonomi makro, skema subsidi untuk biodiesel memerlukan evaluasi ketat. Pemerintah selama ini memberikan dana insentif dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada perusahaan penghasil biodiesel. Namun, manfaatnya terhadap publik masih dipertanyakan.
Banyak pihak menilai bahwa skema ini cenderung berpihak pada korporasi besar, bukan pada pengurangan emisi atau penghematan biaya energi masyarakat. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, subsidi biodiesel berisiko menjadi beban fiskal tanpa kontribusi berarti terhadap ketahanan energi nasional. Swasembada energi semestinya tidak hanya menjadi proyek jangka pendek bersifat politis, melainkan bagian dari strategi jangka panjang menuju keberlanjutan.
Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola energi secara holistik: mendorong riset dan inovasi, memperluas adopsi teknologi hijau, membangun kapasitas SDM energi bersih, serta merancang regulasi yang melindungi lingkungan dan masyarakat. Pengembangan energi alternatif tidak bisa bergantung pada logika pasar semata, tetapi harus dikawal dengan etika dan visi ekologi yang kuat.
Penting juga untuk membangun kesadaran publik bahwa kemandirian energi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Masyarakat perlu diajak untuk hemat energi, beralih ke moda transportasi rendah emisi, dan terlibat dalam gerakan transisi energi rakyat. Di sinilah peran edukasi, literasi energi, dan partisipasi komunitas menjadi sangat vital. Tanpa partisipasi publik, ambisi swasembada energi hanya akan menjadi wacana elitis yang jauh dari kenyataan.
Dengan demikian, swasembada energi bukan perkara menekan angka impor semata, melainkan menyusun ulang orientasi kebijakan energi nasional agar lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan. Biodiesel bisa menjadi bagian dari bauran energi, tetapi tidak sepatutnya menjadi satu-satunya tumpuan. Dalam dunia yang terus berubah, ketahanan energi sejati hanya bisa dicapai melalui keragaman sumber, ketangguhan sistem, dan kesadaran kolektif.